
Aku berteman dengan novelis Leo Pasar di Yogyakarta pada tahun 1990. Saat itu usiaku 19, Leo dua tahun lebih tua.
Kami berdua kelayapan di Malioboro dengan sepeda motor bututnya. Kami merasa menjadi seniman dengan berteman dengan para mahasiswa di ISI. Kami juga mengaku sebagai sastrawan karena berteman dengan sejumlah penyair dan penulis. Kami juga sering ikut membantu pameran di galeri yang bertebaran di seantero Yogya atau resital tari dan musik sebagai tugas akhir para sahabat.
Kadang untuk sekadar penyambung hidup, saat tidak ada job, aku dan Leo menjual darah di rumah sakit. Atau jadi figuran numpang lewat di film yang kebetulan syuting di kota itu.
Pokoknya, sebisa mungkin menjadi kreatif dalam mencari nafkah.
Aku ingat pertama kali berjumpa Leo. Saat itu aku menemani gadis-gadis dari Fakultas Sastra jurusan Sastra Perancis ke pesta yang diadakan AFY. Karena kesukaanku kepada komik Belgia dan Alain Delon maka aku bisa berbicara sedikit bahasa Prancis. Mereka menjagaku seakan aku anak singa yang harus dilindungi, membuatku sulit untuk jatuh cinta dengan salah satu dari mereka.
Aku berharap di mata orang lain sebagai alpha male di kawanan babun, tetapi sebenarnya mereka hanya butuh seorang cowok di sekitar bisa disuruh-suruh.
Mereka tahu di mana semua peristiwa seni berlangsung dan kami pergi ke pembacaan puisi di tempat ini di konsulat Prancis di jalan Sagan suatu malam. Aku biasa menonton film tanpa sensor dan membaca komik-komik dewasa di situ.
Bisa dikatakan, acara itu adalah pertemuan para penyair ‘revolusioner’ dan Leo ada di sana dengan pipa cangklong dan kumis berantakan seperti sikat WC, dengan aksen yang semual kukira Bali tapi ternyata Aceh. Aku rasa dia menganggap dirinya Dada dalam puisi.
Setengah dari kata-katanya tak bisa kumengerti, tapi kumis dan matanya yang kelabu mampu melakukannya: orang ini memiliki seni sejati. Karisma yang membara sama seperti yang kini kamu lihat di sampul buku-bukunya yang berdebu.
Aku katakan kepadanya betapa aku menyukai puisinya, membelikannya croissant, sepotong keju camembert dan sebotol bir, dan kami berteman sejak saat itu.
Kami tidak pernah punya uang karena kami ingin menjadi penyair. Bokek adalah bagian dari menjadi penyair. Dengan baju tebaik yang kami punya, kami sering menyelinap ke acara-acara resepsi pernikahan di hotel atau tahlilan di surau.
Kami selalu membicarakan tentang Chairil, Iwan Simatupang,Rendra. Kami selalu berbicara tentang Beauvoir, Camus dan Rimbaud.
Pernah satu kali kami berada di lembah dekat Fakultas Peternakan. Di sana ada kandang ayam untuk praktik mahasiswa. Jadi Leo punya ide dan kami pergi ke pasar Kranggan membeli satu ons bawang putih. Kemudian kami kembali ke kandang ayam di sisi lembah dan melemparkan bawang putih ke dalamnya. Ayam yang mematuk bawang putih tersebut langsung teler. Mudah saja bagi gari menjebol dinding kawat dengan tang gunting yang dibawanya.
Leo menerobos dan melompat menerkam dua ekor ayam yang tak mampu lagi berkotek atau kabur. Menyembunyikannya ke balik jaket kulitnya dan kami berlari keluar. Bulu-bulu beterbangan ke mana-mana dari tubuh Leo.
Kami kembali ke pasar Kranggan untuk menyembelih hewan-hewan malang tersebut. Untuk upah meminjam pisau kami membayarnya dengan jeroan dan ceker.
Kemudian kami pergi ke rumah yang dikontrak oleh gadis-gadis Sastra Prancis di Pringwulung dan membakar ayam di kompor mereka. Leo pernah bekerja sebagai jongos di rumah makan Padang. Ayam bakar itu lezat.
Seniman revolusioner bukan hanya aku dan Leo. Masih ada segerombolan penyair dan anarkis atau jenis lainnya. Ada yang dari Sampang, Tarutung, Payakumbuh, Bugis, Banjar, Ternate, dan dari sekitar Yogya sendiri.
Tempat terbaik untuk bertemu adalah di benteng Vrederburg ujung jalan Malioboro. Selalu ada orang baru. Juga ada tempat di jalan Bantul yang suka kukunjungi sendiri untuk menyepi dan gadis di belakang bar adalah orang Sunda-Batak. Orangnya jangkung dan riang dengan hidung mancung dan kacamata besar. Rambutnya diikat ekor kuda seperti murid SMP aku jatuh cinta padanya.
Kami berbicara berjam-jam tentang apa saja dan kemudian aku mengatakan padanya aku ingin menikahinya. Sampai suatu hari Leo datang dan menemukanku di sana. Setelah beberapa gelas bir dia berkata:
"Cewek itu mukanya seperti kuda. Persis seperti kuda. Muka kuda yang panjang. Sepertinya bapaknya kawin dengan kuda betina. Aku kira kalau dia ikut pacuan kuda dia bisa menang, setidaknya juara tiga."
Sampai matahari terbit Leo terus mengoceh seperti itu.
Tapi secara garis besar, kisahku dan Leo seperti ini:
Kami menerima pekerjaan mengecat pagar rumah dan kami kehabisan cat. Jadi pemilik rumah menyuruh aku dan Leo menyusuri jalan ke toko bangunan di Janti. Begitu keluar dari toko dan menyeberang jalan, sebuah mobil VW merah kecil penuh dengan penumpang nyaris menabrak kami. Suara rem yang diinjak mendadak mendecit panjang.
Dengan pipa cangklong terselip di bibir dan tanpa kehilangan kesabarannya atau perubahan ekspresi, ia mengelurakan asap dari hidup dan mengacungkan tinju pada mobil itu. Lalu kami melanjutkan pembicaraan tentang Sapardi Djoko Damono dan Pablo Neruda.
Di tengah jalan, seseorang mengetuk pundak kami. Seorang pemuda Timor berambut pirang gimbal. Mobil VW merah kecil yang penuh dengan orang-orang sedang berhenti di belakang kami.
"Kau yang tadi yang memberi kami tinju?" tanyanya.
"Iya," jawab Leo.
"Dasar bajingan," dan dia meninju pipi Leo. Dari kecepatan dan bunyi angin yang ditimbulkan, itu jenis pukulan yang bisa membelah batu gunung.
Sebelum aku sadar apa yang sedang berlaku, Leo telah membuka tutup cat dan menghamburkan isinya ke segala penjuru, termasuk kap dan kaca mobil VW merah kecil itu. Kemudian dia mencoba menyalakan geretan.
Pemuda itu melompat masuk ke dalam mobil yang segera melaju. Leo terjungkal ke trotoar.
Ketika dia berdiri, senyum lebar tergambar wajahnya. Dia berkata:
"Tidak sia-sia hobiku nonton film mafia Italia."
Ketika Kantata Takwa datang ke Solo, Leo dan aku berangkat menumpang truk. Untuk membeli tiket masuk, kami bekerja di sebuah rumah makan ayam goring yang biasa melayani wisatawan.
Kami melayani meja yang penuh orang asing dekil, suka melempar-lempar makanan.
Setelah satu jam kemudian Leo berkata:
"Kerouac terbatuk-batuk dan Balzac terbahak-bahak melihat kita jadi jongos."
Ditambah lagi, pemilik rumah makan itu mengumpulkan tips yang seharusnya untuk kami.
Kami bekerja di lantai dua. Bagian belakang menghadap lorong dan bak sampah besar berada di bawah balkon. Sambil beristirahat sejenak di sana kami mendapat ide untuk melarikan diri.
Aku dan Leo memiliki ide yang sama. Jadi kami masuk lagi dan mengumpulkan uang pembayaran yang ditinggalkan para pelanggan di meja, lalu menggantung di pagar balokn dan menjatuhkan diri ke bak sampah. Kami lari dari sana.
Kami menghitung hasil jarahan malam itu di rumah Tuti, gadis Sastra Prancis putri asli Solo, dekat Taman Bale Kambang. Lebih dari enam ratus ribu rupiah.
Lusanya kami naik kereta api ekonomi di pagi hari menuju pulau Dewata. Dari Ketapang menyeberang dengan kapal feri ke Gilimanuk dan dilanjutkan dengan bus ke Denpasar.
Aku dan Leo menyewa kamar wisma di Kuta. Kami tinggal di sana beberapa minggu, minum, menulis puisi di meja ruang lobi. Tidak ada orang lain di sana karena belum musim liburan. Aku dan Leo bahkan jarang bicara satu sama lain.
Kami melewatkan hari-hari dengan berjemur di pantai dan menikmati keindahannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup kami hanya duduk dan menulis.
Kemudian Leo bertemu guru Selandia Baru di pub. Dia sedang berlibur dank arena bukan peak season mendapatkan diskon hingga 70 persen.
Dia suka kumis Leo yang seperti sikat dan pipa cangklong dan obrolan tentang sastra. Dia mengajak Leo ke ke Christchurch, dan itu terakhir kali aku melihat Leo.
Ada satu hal tentang Leo yang tak pupus dari ingatanku. Saat menulis, dia takkan terganggu oleh apapun yang sedang terjadi sambil mulutnya tak henti-henti bergumam: "Rasa itu. Perasaan itu."
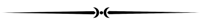
Sepuluh tahun kemudian, saat menjadi pengajar kursus menulis di Jakarta dan masih berjuang untuk menyelesaikan novel pertamaku, ketika berjalan melewati jendela tampilan toko buku Gunung Agung, ada novel karya Leo Pasar.
Aku berdiri menatapnya sambil mengeluarkan payung lipat dari tas ranselku.
Hujan menetes, musim berganti.
Banda Aceh, 5 Juni 2018
Story yang bagus. Bisa dijadikan snopsis filem. Dialognya asik dan cocok untuk diangkat ke layar lebar
cerita yang sanggt menarik bg
Cerita yang menarik 😊😊
Hmmm ajari bang cara buat nya
hahahaha. ini ceritanya seru!
Kiat yang dibagi singkat saja. Tapi memukul. Lebih keras dari pukulan pemuda Timor yang melesat ke pipi Leo.
Jadi penasaran ini fiksi atau betulan. Haha
Cerita fiksi yang istimewa,...
Luar biasa ceritanya bang @ayahkasih
Ditunggu poatingan berikutnya bang
Keren ayah, saya suka
Luar biasa karya @ayahkasih. Seru ceritanya