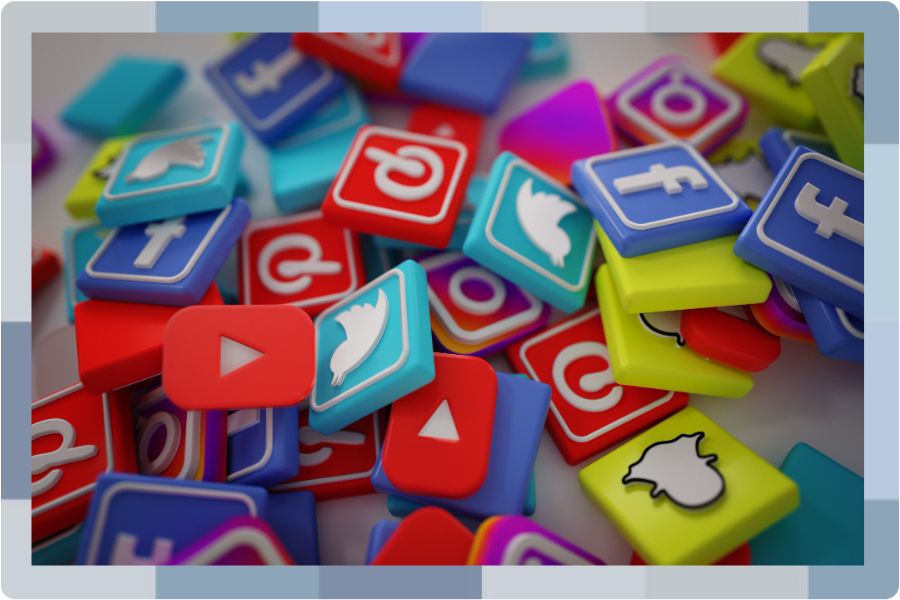
Ketika mendengar frasa “media sosial”, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Apakah terkait dengan Instagram, TikTok, dan X (baca: Twitter)? Atau, tentang sarana untuk pengembangan diri, karena di sana kita dapat berekspresi, sekaligus mengonsumsi berbagai informasi yang dibutuhkan?
Jika kalian menjawab salah satu atau keduanya, tentu tidak salah. Dalam banyak literatur, penjelasan semacam itu memang valid adanya. Namun, bagaimana kalau saya menyebut media sosial adalah jebakan pengembangan diri? Saya yakin, sebagian dari kalian akan memicingkan mata.
Iya, klaim saya tersebut memang terlihat menyeramkan. Seolah-olah, media sosial memiliki semacam virus, yang diam-diam bisa meracuni penggunanya. Tapi tenang saja, klaim saya itu tidak datang dari ruang hampa. Ada beberapa alasan logis, yang bisa kita diskusikan sebelum menyepakati atau menampiknya.
Media Sosial sebagai Ruang Ekspresi sekaligus Eksplorasi
Sebelum membahasnya lebih dalam, kita perlu pertegas dulu terkait definisi media sosial. Ada satu buku yang cukup kuat untuk kita jadikan rujukan, yakni buku berjudul “Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi” karya Rulli Nasrullah (2015).
Menurut Rulli Nasrullah, media sosial adalah platform teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berpartisipasi. Ketiga aktivitas itu bebas dilakukan oleh pengguna sesuai dengan motifnya masing-masing. Entah itu untuk edukasi, atau sekadar eksistensi diri.
Dari situ—sebagaimana kita singgung di awal paragraf—benar bahwa media sosial itu sebagai sarana pengembangan diri. Sebab dengan media sosial, kita tidak hanya dimudahkan untuk berekspresi, tetapi juga mengeksplorasi banyak sekali konten pengguna, yang dapat kita jadikan inspirasi dalam membentuk diri.
Dua Mata Pisau Media Sosial yang Perlu Kita Tahu
Semua kemudahan tersebut, menurut Rulli Nasrullah (2015), dimungkinkan karena media sosial punya kekuatan utama yang disebut dengan user generated content (UGC). Mudahnya, UGC adalah fasilitas yang memungkinkan individu mengakses teknologi tanpa ada batasan apapun, kecuali jika tanpa jaringan internet.
Nah, sialnya, UGC ini tidak seutuhnya membawa manfaat. Ia bisa dibilang memiliki dua mata pisau; di satu sisi memudahkan pengguna, tapi di lain sisi juga berpotensi merugikan. Mengapa bisa demikian?
Sederhananya begini. Efek yang ditimbulkan dari UGC ini, membuat pengguna media sosial memproduksi konten tanpa filter standarisasi tertentu. Nah, karena kejernihan kontennya tidak menentu, otomatis membuat kita sulit untuk mengambilnya sebagai inspirasi pengembangan diri.
Tidak mungkin, kan, kita mengasah potensi diri berdasarkan informasi yang keliru?
Algoritma Media Sosial, Coping Mechanism, dan Echo Chamber
Masalahnya belum cukup sampai di situ. Kondisinya semakin diperparah dengan algoritma media sosial.
Ya kita tahu sendirilah, bagaimana cara kerja algoritma medsos. Konten apa yang paling banyak like dan waktu tontonnya, maka konten itu pula yang akan disarankan kepada pengguna. Ringkasnya, algoritma medsos tidak peduli apakah sebuah konten itu edukatif atau tidak.
Pada titik tertentu, ketika emosi dan pikiran kita dalam kondisi netral saat mengonsumsi konten, mungkin algoritma media sosial bisa bersahabat. Tapi kalau tidak, misalnya saat lagi stress dan butuh coping mechanism, di situ jebakan medsos datang. Kita sering kan, lagi sumpek sama kerjaan, tapi larinya ke medsos buat nonton konten alih-alih validasi perasaan.
Ini jangan dianggap sepele. Sebab coping mechanism ini, menurut halodoc, bisa terjadi secara sadar ataupun tidak. Mekanisme pengelolaan emosi ini pun tidak selalu positif atau negatif. Ia mengikuti kedewasaan manusianya.
Oleh karenanya, kita perlu hati-hati saat melakukan coping mechanism. Sebab itu amat sangat berpotensi membuat kita jatuh pada jurang echo chamber. Menurut Wulandari, Rullyana, dan Ardiansyah (2021), echo chamber adalah kondisi ketika kita hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan diri sendiri.
Kondisi tersebut tentu saja berbahaya dalam pengambilan keputusan. Apalagi, jika konteksnya untuk mengembangkan atau mengasah potensi diri.
Mengantisipasi Kecelakaan Logika dalam Bermedia Sosial
Pertanyaannya kemudian: Lantas bagaimana solusinya agar terhindar dari kondisi semacam itu?
Kalau kita lihat dalam kajian logika, kondisi semacam itu pada akhirnya disebut sebagai bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari bukti atau informasi yang mendukung kepercayaannya sendiri, dan mengabaikan informasi lain yang justru lebih benar.
Untuk mengantisipasi kecelakaan logika semacam itu, saya punya saran berdasarkan pengalaman pribadi.
Pertama, ikutilah akun media sosial para pakar dari berbagai bidang yang menurut kalian informasinya dibutuhkan. Media sosial dalam hal ini bisa apa saja; entah itu Instagram, TikTok, atau X. Tergantung preferensi kalian masing-masing.
Lalu yang kedua, dalam kondisi apapun, biasakan untuk selalu curiga pada konten-konten yang muncul di timeline media sosial kalian. Entah itu dari pakar atau tidak, tetap curiga. Ini bukan berarti menolak kepakaran sebagaimana disebut oleh Tom Nichols, ya. Tapi untuk melatih nalar kita untuk tetap aktif mencerna informasi di media sosial.
Kemudian yang ketiga, jangan anggap medsos sebagai sumber ilmu atau pengetahuan. Ingat, medsos itu punya keterbatasan durasi video maupun jumlah kata. Sangat jauh berbeda dengan artikel dan buku. Maka, selain terbiasa untuk curiga, juga biasakan untuk membaca literatur teks.
Tentu saran saya ini tidak lantas menghilangkan potensi jebakan media sosial. Tapi setidaknya, dengan tiga hal itu, saya bisa menjamin kecil kemungkinannya kalian terjerumus ke jurang echo chamber.
Tidak percaya? Silakan buktikan sendiri hasilnya.
"Karya ini dibuat untuk Lomba Menulis Blog dalam rangka 1st Anniversary MenulisID"